Memanfaatkan waktu luangnya, Herman Omordow membuat ukiran dengan segenap hati. Kesetiaannya melestarikan ukiran Asmat, membuat dia pernah dianugerahi penghargaan dari negara tahun 2011 silam.
Bertelanjang dada, Herman Omordow (61) serius mengetuk-ngetuk pahat kecil ke lempengan kayu berukuran 30 sentimeter x 15 sentimeter di hadapannya. Sesekali dahinya mengernyit untuk memastikan motif ukiran yang sudah ia bentuk. Penuh ketelatenan, lempeng kayu itu perlahan membentuk ukiran burung kasuari.
“Biasanya satu ukiran seperti ini, kalau fokus, bisa selesai dua hari saja,” ujar Herman, pada Rabu siang yang terik, saat pertengahan Oktober silam, ditemui di kampungnya.

Herman Omordow (61), sedang memahat sebuah ukiran di Kampung Er, Distrik Sawaerma, Kabupaten Asmat, Papua, Rabu (13/10/2021).
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Fokus yang Herman maksud adalah mengerjakan sehari penuh, tanpa diselingi pekerjaan lain. Jika ada kesibukan untuk bekerja atau pergi pangkur sagu, ukiran itu baru bisa selesai seminggu. Ukiran yang Herman kerjakan saat itu adalah murni untuk mengisi waktu luangnya. Jika ada kolektor atau turis datang, ukiran tersebut kerap ia tawarkan untuk dijual.
Baca juga : Arkilaus Kladit, Menjaga Hutan untuk Masa Depan
Herman adalah salah satu pengukir termasyhur Suku Asmat dari Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Papua. Ia hanya mengukir dengan delapan alat ukir berbagai bentuk dan satu buah batu yang berfungsi sebagai alat ketuk. Meski demikian, karya-karya Herman sungguh memesona dengan detail dan bentuk yang rumit dan rapi.
Nama Herman berkali-kali muncul sebagai juara dalam Festival Budaya Asmat di bidang seni ukir. Festival tahunan yang diadakan sejak 1981 ini merupakan perayaan akbar budaya Asmat yang diikuti oleh seluruh kampung. Ratusan pengukir atau dalam bahasa asmat disebut wow ipits turut dalam festival tersebut. Penghargaan bagi karya terbaik tak main-main, hingga puluhan juta rupiah.
Turun-temurun
Kampung Er, Distrik Sawa Erma, tempat Herman tinggal, bisa ditempuh sekitar satu jam menggunakan perahu motor bermesin dari Agats, pusat Kabupaten Asmat. Layaknya kampung lain di Asmat, kampung itu berada di atas rawa. Rumah-rumah kayu warga berupa panggung dengan tiang penyangga. Untuk berpindah dari rumah ke rumah, warga harus melalui jembatan kayu.
Jauh dari hiruk pikuk kota, membuat transfer keterampilan mengukir di sana berjalan alami dan sangat kuat. Herman yang tak lulus SMP itu hanya mengandalkan ingatan dan praktik sepanjang hayat. Saat kecil, ia sering memperhatikan sang kakek (tete) mengetuk-ngetukkan alat ukir ke papan kayu.
Herman memerhatikan setiap detail ketukan, arah alat ukir, hingga motif-motif yang terbentuk. Ingatan itu kian menguat seiring banyaknya waktu yang Herman habiskan untuk melihat kegiatan tersebut.

Deretan ukiran dan patung koleksi Museum Kebudayaan Asmat di Agats, Papua, Senin (11/10/2021). Museum tersebut menyimpan sekitar 700 koleksi patung dan ukiran hasil karya masyarakat Asmat. KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Dengan alat yang tersedia di rumahnya, Herman kemudian mencoba mengukir bilah kayu yang ia cari dari hutan. Ingatan-ingatan tentang posisi alat ukir, lekukan motif, hingga kerasnya ketukan sang kakek, ia coba praktikkan.
Sang pengukir patung membuat patung itu untuk mengekalkan ingatan bahwa anggota keluarganya pernah terbunuh dan sang pengukir yang masih hidup akan membalaskan dendam.
Dari obrolan-obrolan itu, ia jadi mengerti bahwa ukiran dan patung Asmat amat erat dengan pesta atau ritual adat. Pada masa silam, patung-patung Asmat dibuat sebagai motif balas dendam. Misalnya, jika ada anggota keluarga yang tewas saat perang antarsuku, anggota keluarga yang masih hidup membuat patung itu untuk mengenang.
Sang pengukir patung membuat patung itu untuk mengekalkan ingatan bahwa anggota keluarganya pernah terbunuh dan sang pengukir yang masih hidup akan membalaskan dendam. “Itu dulu, sekarang kami buat patung untuk mengenang tete–nene yang sudah meninggal, tidak untuk balas dendam,” katanya.

Selain itu, ada pula perisai yang pada masa silam digunakan untuk perang. Perisai satu lempeng itu tingginya bisa mencapai dua meter yang terbuat dari akar pohon besar. Bagian muka perisai terdapat berbagai ukiran dan memiliki makna tersendiri. Salah satunya, ukiran hiasan hidung suku Asmat yang menyerupai bulan sabit.
Simbol itu memiliki arti kebesaran seseorang sekaligus untuk menakut-nakuti lawan. Di bagian kepala tameng di Distrik Sawa Erma terdapat semacam lempeng lingkaran kecil. Itu merupakan simbol ikan pari yang memiliki arti perlindungan. Motif tersebut juga memberi semacam sugesti keberanian bagi orang yang memegang tameng.
Mengajarkan ke pemuda
Saat memulai sebuah ukiran, Herman melantunkan doa di dalam hati. Ia memanggil roh leluhur yang sudah tiada. Di dalam benaknya, ia membayangkan masa-masa indah ketika bersama almarhum kakeknya yang mengajarinya mengukir.
“Setelah itu, perasaan menjadi semangat bekerja. Ada keinginan keras. Itu tandanya tete sudah hadir,” ujar Herman.

kampung Er, Distrik Sawaerma, Kabupaten Asmat, Papua, yang dikelilingi sungai, Rabu (13/10/2021).
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Ia meyakini, kehadiran roh leluhur itu ditandai dengan banyak hal. Misalnya, melalui suara cicak yang bersahutan saat dia mulai mengukir. Tanda-tanda itu menjadi penyemangat bagi wow ipits sepertinya untuk menyelesaikan ukiran dengan baik.
Pengetahuan dan pengalaman itu Herman ajarkan kepada pemuda dan anak-anak di kampungnya. Siapa saja yang ingin belajar, bisa datang langsung ke rumahnya. Herman akan dengan senang hati memberi segala pengalaman yang ia miliki, tanpa memungut bayaran.
Berkat dedikasi itu, saat ini Distrik Sawaerma dikenal sebagai salah satu pengukir-pengukir ulung Asmat. Sejumlah ukirannya dapat dilihat di Gereja Kristo Amore. Gereja yang sepenuhnya terbuat dari bahan kayu itu tampak artistik karena penuh dengan ukiran Asmat karya warga di sana.

Para lelaki beristirahat di dalam jew atau rumah bujang masyarakat Asmat di Kampung Er, Distrik Sawaerma, Asmat, Papua, Rabu (13/10/2021). Tiang kayu jew dipenuhi dengan ukiran yang dibuat oleh para pengukir handal di kampung tersebut. KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Oleh karena kegigihan dan konsistensinya melestarikan ukiran Asmat, Herman mendapat penghargaan dari negara pada 2011. Kala itu, ia diundang ke Istana Presiden untuk menerima Bintang Budaya Parama Dharma, tanda kehormatan yang dianugerahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati seseorang atas jasanya dalam bidang kebudayaan.
Susilo Bambang Yudhoyono, presiden kala itu, memberikan penghargaan langsung kepada Herman. Ia bersanding dengan tiga penerima tanda kehormatan yang sama, yakni pelukis Basoeki Abdullah (alm), sastrawan Abdullah Idrus (alm), dan seniman Titik Puspa.
Masa perang antarsuku kini sudah berakhir sejak didirikannya gereja Katolik pada 1953 dan intervensi dari perintah di Asmat. Sebagai wow ipits yang masih bersetia mengukir, Herman turut melestarikan nilai-nilai yang baru dalam ukiran, sesuai perkembangan zaman.
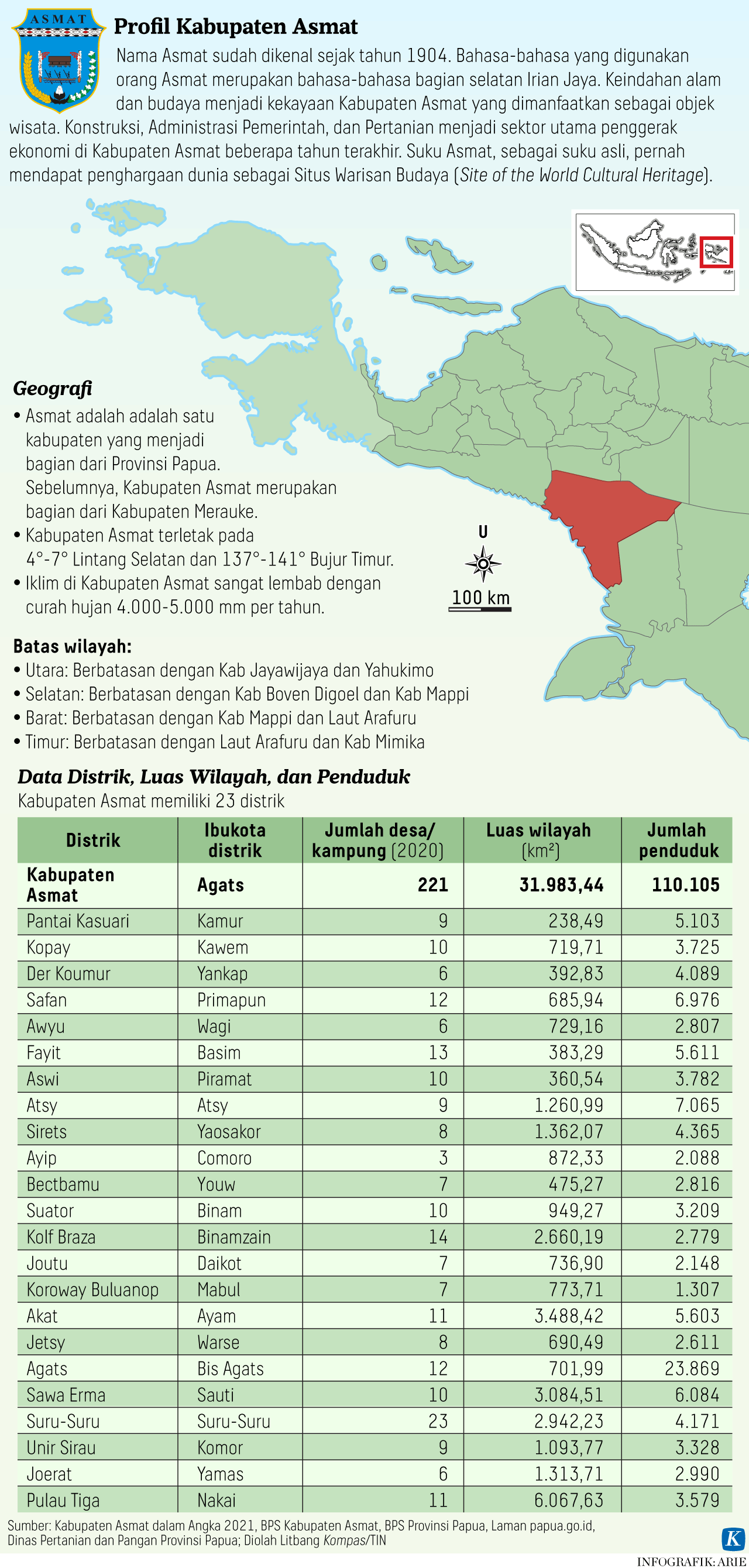
Saat ini, selain digunakan untuk ritual adat, ukiran Asmat juga kerap dipesan oleh kolektor seni atau wisatawan. Meskipun tak melulu ada pesanan kepada pengukir seperti Herman, ia tetap mengukir dan mengajarkan keterampilannya kepada anak-anak di kampungnya.
“Ini cinta kasih kami kepada tete, nene, bapa, mama yang sudah meninggal. Harapan saya, nilai-nilai baik itu terus ada. Seperti motif ekor kuskus, yang artinya hubungan yang erat,” tutur Herman. (Sucipto/Dionisius Reynaldo Triwibowo)
Biodata :
Nama : Herman Omordow
Tempat, tanggal lahir: Asmat, Tahun 1960
Penghargaan : Bintang Budaya Parama Dharma 2011



